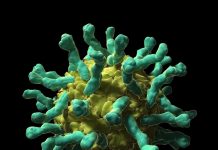Akhirnya aku telepon dia, ‘Nto. Halo, sahutnya, tiga kali. “Halo…halo…halooo…” suaranya begitu.
Gila nggak, sih, ‘Nto, aku nekat begitu? Mungkin nggak, bisa jadi iya. Tapi, ‘Nto, kamu tau persis ‘kan, cinta bergelayut di sekujur jiwa-tubuh-yang-ada ku. Bergelayut dari pucuk ubun-ubun hingga akar jemari kaki, seperti kawanan kelelawar merimbuni langit-langit dan stalaktit gua, menghitam kelam, melekat pekat. Cinta itu.
Memang aku nekat, ‘Nto. Tapi, takkah kau sadari sekian panjang waktu mengembangbiakkan rasa rindu menyakau yang memurukkanku dalam lorong panjang di dasar palung terjal kesenyapan lautan waktu-waktu ku? Sementara ombak kehadirannya serasa jelas sekali berbuih berdebur di atas sana. Di atas sana, dengan liukan angin dan siraman matahari, beserta langit biru cerah ditaburi putihnya awan melingkupi. Takkah, ‘Nto?
Maka, meski aku telah berjanji tak akan, aku telepon dia, ‘Nto. Jari-jariku tak membutuhkan otakku untuk menekan nomor-nomor itu. Jemariku bergerak menari dituntun syaraf kebiasaan. Lalu dia bersuara. Halo, sahutnya, tiga kali. “Halo…halo…halooo…” suaranya begitu.
Kamu pasti tau, ‘Nto, lelaki berwajah keras seperti aku, sejatinya adalah binatang lemah dan mudah tergoyah. Cemen, seperti sering kau bilang sambil menyemprotkan asap rokok ke mukaku. Tapi, dengarlah pengakuanku, cintaku dalam dan terus menukik tajam, semakin mendalam. Namun, iya, aku mengaku, telah kuabaikan cinta dalam kesabar-lembut-tulusannya. Telah kuhambur-hamburkan cinta dalam kesabar-lembut-tulusannya, pada sekian lama panjang waktu bergulir.
Maka, terjadilah sebuah pagi pada pagi itu. Aku tersentak persis seperti tempo hari kesetrum listrik kipas angin sontoloyo itu. Aku tersedak seperti tempo hari ketika keselak biji duku kecut murahan itu. Untuk kemudian terkapar, ‘Nto, terengah telentang engap-engapan. Seperti ketika kita usai show off di lintasan Senayan, berlari sore mengiringi Mirna bahenol bernapas kuda, kenalan baru kita itu.
Aku tersentak-sedak, ‘Nto, terkapar-lentang, terengap-engah, ketika dia katakan bahwa cinta dalam ketulus-lembut-sabarannya telah kering mengerontang, karena sekian lama telah aku hambur-hamburkan, telah aku foya-foyakan, tanpa cinta. Maka dia akan pergi.
Namun, aku adalah lelaki angkuh dari pulau seberang, panjang perjalanan waktu dan ruang telah aku rambah. Aku tegar senantiasa, kakiku kokoh, dadaku busung, kepalaku pantang tunduk-lemah, mataku tajam menyorot, tiada waktu buat menyayu-redup. Tentu, tak perlu aku minta dia berfikir ulang. Jelas, haram hukumnya aku bermohon supaya dia untuk tetap bersamaku.
Maka, pergilah dia, dengan lembut mengucapkan selamat tinggal. Pagi-pagi sekali waktu itu, ‘Nto. Udara masih berselimut embun. Dua tiga kupu-kupu masih bercengkerama berlarian disela-sela pohon delima di depan rumah kos kita, sebelum debu dan hentakan matahari Jakarta menyembunyikan mereka entah dimana.
Pagi-pagi sekali waktu itu, ‘Nto. Bahkan mbok Ina penjaja cakwe belum lewat, Pak Andang baru limabelasan menit kembali dari subuhan di musholla. Pagi-pagi sekali, mbak Sumi belum selesai nyuci di belakang, dan Sherly baru saja pulang dari malam panjang di Kemang.
Dia pergi melangkah untuk melangkah pergi. Meski berusaha cool, aku mengamati langkah kakinya menuruni tiga anak tangga depan rumah kos kita, menutup pagar. Kemudian tubuh mungil yang entah berapa ratus kali sudah aku dekap itu hanya meninggalkan punggungnya dalam tatapanku, hingga tikungan menuju mulut gang menelannya lenyap tak berbekas. Sebuah ojek melintas, gemuruh suaranya menghentikan tatapan nanarku.
‘Nto, kamu pasti tahu ‘kan, waktu berjalan, lelaki dari pulau seberang ini mulai limbung. Kakiku makin lama makin gemetar, pijakannya goyah. Aku kehilangan cara membusungkan dada, menegakkan kepala. Kamu sering bertanya ‘kan, ‘Nto, kemana sorot mata percaya diri tajam penuh optimisme itu.
Tak butuh waktu lama aku menyadari, ‘Nto. Semuanya pergi bersama dia, bersama catatan perjalanan, bersama segunung rasa bersalah menggumpal di sesaknya dada.
Namun, ketika aku belum mampu untuk berfikir menebus semuanya, dia datang. Dia datang padaku. Pagi-pagi juga waktu itu. Matahari sekonyong-konyong bersinar hangat di kamar kosku. Dua puluh tujuh tangkai mawar sontak mekar serentak, mewangi semerbak menghentak-hentak. Canon in D dari Johann Pachelbel mengalun dalam liukan flute dan harpa, tujuh peri cantik bersayap putih berdansa menari di sekelilingku.
Aku tak mampu untuk tidak tersenyum sedemikian lebarnya, dan menyinarkan cahaya mata terterang sepanjang zaman. Jiwa dan ragaku menyumringah tiada tara. “Hai Neng, apa kabar?”
Namun, begitulah, roda pedati masih menggelinding ke bawah, menggilasku tanpa belas kasihan tepat di selangkangan. Godam nasib menghantam jidatku telak-telak, plak! Aku terlempar ke atas untuk kemudian terjengkang terkangkang tertelentang. Plafon kamarku luluh lantak berserak-serak, rimbun menimbun jasadku. Aku tak berdaya, ‘Nto.
‘Nto, adakah hal yang lebih buruk daripada menjilat ludah dan dahakmu sendiri? Adalah ketika kau menjulurkan lidahmu dengan airmata terurai, ludah dan dahak itu telah lenyap dibersihkan malaikat dan bidadari. Aku rasanya ingin menjerit berteriak memohon pada Yang Kuasa untuk mengembalikan sepercik ludah dan dahak itu, agar cerita ini dapat berubah. Namun, aku tahu itu tidak akan pernah dapat terjadi karena dia telah menemukan seseorang.
Oh, Ibu, aku adalah lelaki kalah di tengah hiruknya Jakarta.
Lebih baik kau diam saja, ‘Nto, tak ada gunanya basa-basimu. Singkirkan segelas alkoholmu, tawaran sebatang rokokmu buang saja jauh-jauh. Dan dengar, baiknya kau juga menyingkir. Aku maafkan kau, tapi aku tak mampu lagi bicara padamu. Aku tak mampu lagi bicara pada siapapun. Yang aku inginkan adalah lari menjauh dari semua ini, lari ke ujung bumi yang aku tahu tak berujung, karena aku hanya ingin lari, lari jauh. Tapi, aku tak berdaya dalam kesekaratanku.
‘Nto, aku tak hanya kehilangan dia, aku juga akan kehilanganmu, walau terus terang aku tak begitu peduli padamu. Tapi percayalah, aku tak pernah marah padamu, asal kau jaga dia baik-baik.
Namun, ‘Nto, kau tahu cinta yang bergelayutan itu? Yang hitam menebal di sekujur jiwa-tubuh-yang-ada ku? Yang bagai kawanan kelelawar merimbuni stalaktit gua? Yang makin hitam menebal beranak-pinak melekat-pekat?
Dan, meski empat tahun hampir sudah berlalu, engkau tahu rindu yang mendekapku erat-erat dan memagutku kuat-kuat itu? Rindu yang memurukkanku dalam lorong gelap panjang dingin beku di dasar palung samudera Hindia? Aku meringkuk menggigil! Aku rindu! Aku sakau! Aku sekarat! Aku menangis…
Maka, maafkan aku. Meski aku telah berjanji tak akan, ketika Padi mengalunkan seuntai kasih yang tak sampai dari sudut kamarku, akhirnya aku telepon dia, ‘Nto. Halo, sahutnya, tiga kali. “Halo…halo…halooo…” suaranya begitu. Aku melambung tinggi, menembus langit-langit kamar, menembus kamar lantai atas, menembus atap rumah kos, tujuh buah antena tivi berhamburan rontok, aku melayang di antara sekumpulan awan malam bermandikan bintang…
Sayup masih aku dengar suaranya, “Halo…halo…halooo…”.
Klik.
*****
*** Seri Pujangga:
- Melintasi Embun
- Angin Melayang Lewat Jendela Tak Berkaca
- Bidadari yang Jatuh dari Langit Montreux
- Di Pesisir Malam Angin Beterbangan di Atap-atap Rumah, Bergentayangan di Pucuk-pucuk Kelapa
Salam, Riki Frindos – www.FrindosOnFinance.com![]()