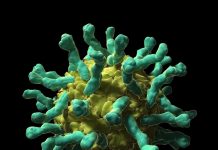Ayah memang tak banyak bicara, tak banyak bertanya, juga tak banyak tertawa, apalagi menumpahkan airmata. Ya, sesekali ia mengajakku berjalan, sesekali ia bercerita. Ayah terlihat sedikit jauh, tapi aku merasa dekat padanya.
Dan, ayah seorang yang pengalah, terutama pada ibu. Mungkin ia sering berbuat salah, yang membuat ibu marah. Atau ibu mudah terpicu amarah karena sakit yang dideritanya. Entahlah. Yang jelas ayah lebih sering diam, mengiyakan, atau meminta maaf pada ibu. Barangkali karena itu, secara sadar atau tidak, aku sangat berempati pada ayah. Terutama sejak malam itu.
Malam itu aku terbangun karena mendengar pertengkaran ibu dan ayah. Tak lama kemudian, aku mendengar langkah kaki ayah keluar dari kamarnya, aku melihat cahaya lampu teplok yang ditenteng ayah melintas di depan kamarku. Ayah berjalan menuju sumur di belakang.
Setelah sekian lama menahan rasa kencing, aku memutuskan segera ke sumur, mumpung ayah ada di sana. Aku kaget melihat ayah duduk di dingklik kecil, di depan sebuah ember besar. Kain sarung ayah tergulung ke atas dan diikatkan ke pinggang. Ayah menoleh sebentar padaku dan mengisyaratkan dengan gerakan kepalanya agar aku buang air kecil di sudut di sebelah kanan.
“Ayah mencuci pakaian?” aku sekedar bersuara.
“Iya,” ayah menjawab dengan wajah datar dan meneruskan mengucek sebuah celana pendek berwarna merah tua, seragam sekolahku.
Sinar lampu teplok yang tergantung di dinding kamar mandi samar-samar menerangi wajah ayah yang mulai berkerut. Angin dingin malam dari Merbabu berhembus ke sini. Aku kembali ke kamar tidur merebahkan tubuh pelan-pelan agar Dimas yang tidur di sebelahku tak terbangun. Aku tak bisa memicingkan mata lagi. Sesekali aku dengar batuk ayah.
***
Aku mencintai ibu seperti aku mencintai ayah. Meski keras, ibu sangat menyayangi anak-anaknya, ibu ingin yang terbaik buat anak-anaknya, ibu ingin anak-anaknya menjadi yang terbaik. Meski tidak suka mengalah, aku yakin Ibu sangat mencintai ayah. Ibu tidak akan segan-segan menjewer telinga kami jika sampai ada yang memakan lauk yang dipersiapkan untuk ayah, apalagi jika lauk itu ayah sendiri yang memasak. Ibu pernah sungguh murka padaku, ketika teguran ayah aku jawab dengan kata-kata yang keras. Ibu tidak mentoleransi sikap sikap anak-anaknya yang tidak menghormati ayah, meski ibu tak bisa mengalah pada ayah.
Aku juga sangat kagum pada ayah. Ayah sangat pintar, ia tahu banyak hal. Semua teman-temanku bilang ayah adalah guru paling pintar di SD kami. Ayah juga sering menjadi tempat bertanya bagi orang-orang kampung, dan mereka terlihat sangat hormat pada ayah. Aku bangga sekali, aku ingin menjadi seperti ayah.
Ayah tidak hanya tempat bertanya bagi warga, tapi juga menjadi tempat mengadu. Waktu itu, misalnya, tetangga minta ayah bicara lagi pada Pak Parjo, agen judi togel di kampung kami.
Aku tahu dari dulu ayah selalu mengingatkan warga untuk tidak terlibat judi togel. Yang pasti memperoleh keuntungan hanyalah bandar dan agennya saja. Ayah bilang, judi togel hanya untuk orang-orang yang kalah, orang yang kalah pada nasib, orang yang kalah pada hidup. Judi togel tidak hanya membawa kerugian uang, tetapi juga kerusakan hidup.
Tapi, diam-diam aku senang mengikuti dan menghapal nomor-nomor togel yang keluar. Sesekali aku ikut nongkrong di warung Pak Parjo, melihat dan menguping orang-orang bercerita dan berdiskusi tentang nomor. Kalau ayah bertanya, aku mengaku di warung Mbok Narti bermain dengan anaknya yang sekelas denganku.
“Ngadiman akhirnya kena empat nomer lho, tapi rejekinya bukan sama Parjo, dia beli sama agen di Tegalrejo,” kata seseorang ketika membahas nomor yang baru keluar.
“Aku sudah tebak, ini kan nomer enam putaran lalu tinggal digeser kekiri sekali, dan angka enam putar balik jadi sembilan. Hari ini Kliwon kan? Nah, Kliwon itu delapan, ya buntut terakhirnya jadi delapan. Sayang aku lagi ndak ada uang kemarin-kemarin,” seseorang yang lain berkomentar.
“Le, nomer dua minggu lalu berapa ya?” Pak Tono, guru olahragaku, bertanya sambil sibuk mencoret-coret di selembar kertas.
“Kosong enam sebelas, Pak,” jawabku cepat.
“Kalau yang pekan lalu tujuh dua tiga enam kan, ya?”
Aku menganggukkan kepala.
Aku pernah bertanya pada Pak Parjo, kenapa orang-orang ramai pasang nomor togel, padahal ayah bilang itu berbahaya, dan hanya untuk orang-orang yang kalah.
“Orang bisa menang dan jadi kaya, Le.”
“Kan kan lebih banyak yang kalah dan jadi miskin, Pak?”
“Lha, kalau miskin dari dulu ya begitu, ndak ikut togel juga miskin. Tapi kalau ikut, kan ada harapan jadi kaya. Bilang sama bapakmu begitu,” Pak Parjo tersenyum setengah menyindir.
Sejak musim paceklik gagal panen, judi togel Pak Parjo justru makin ramai. Nampaknya Pak Parjo benar, ketika hidup makin susah, orang-orang makin butuh harapan. Ah, tapi, aku lebih percaya ayah, judi togel ini merusak, dan hanya-hanya untuk orang-orang kalah. Untuk apa hidup kalau hanya untuk pasrah pada kekalahan.
Yang jelas warga makin resah. Tapi aku dengar ayah tidak mau lagi bicara pada Pak Parjo. Ayah bilang, minta Pak RW yang bicara. Masalahnya, semua orang tahu Pak RW juga suka pasang nomor. Aku sebenarnya kurang setuju dengan ayah, kesannya ayah kalah dan mengalah pada Pak Parjo. Pak Parjo kan bukan siapa-siapa, aku tak sudi ayah kalah padanya.
Tapi ayah barangkali sudah lelah mengingatkan semua orang tentang judi togel ini. Dan, aku tahu sekali ayah juga ruwet dengan berbagai masalah di rumah. Kini, hampir tiap malam aku dengar ayah bertengkar dengan ibu, atau lebih tepatnya aku dengar ibu marah-marah.
Bulan lalu ibu sakit lagi dan dirawat dua minggu di rumah sakit di Semarang. Padahal bulan sebelumnya Mbak Ratih dioperasi usus buntu. Sayangnya juga, Mas Bagas tidak lolos ujian masuk PTN. Ibu ingin Mas Bagas kuliah di universitas swasta saja di Salatiga. Kata ibu, Mas Bagas sebagai anak sulung harus memberi contoh dan semangat.
Aku tahu ayah keberatan, karena utang koperasinya sudah mentok, belum lagi pinjaman sama Pakde Budi. Sepeda motor ayah juga sudah dilego ke diler di Banyusari. Dan, mbak Ratih setahun lagi harus masuk SMA. Namun, Ibu sepertinya akan kecewa sekali jika Mas Bagas sampai tidak bisa kuliah.
Yang aku dengar juga, ayah berjanji akan bicara dengan kepala sekolah untuk dibolehkan ikut menjual buku pelajaran di sekolah.
Tapi aku agak senang karena ayah lebih sering ngobrol denganku belakangan ini. Dan ayah juga tak marah ketika ia melihatku duduk di bangku warung Pak Parjo. Aku kaget sekali waktu itu, ketika menoleh ke samping ada ayah sedang berdiri celingukan. Sepertinya ayah sudah curiga aku suka duduk di sini dan menguntitku kemari. Tapi ayah tidak marah, aku yakin ayah tahu aku hanya senang mendengar obrolan orang-orang dan menghafal nomor-nomor. Ayah hanya menyuruhku pulang segera.
Sore tadi habis main bola di lapangan belakang mushola, aku mampir ke warung Pak Parjo ikut menunggu berita nomor togel keluar dengan beberapa orang lain. Seperti biasa, sebagian besar orang-orang merasa nomor tebakannya hanya meleset sedikit saja. Ada yg dua nomer buntutnya sudah benar, ada yang angkanya benar tapi terbalik urutannya. Juga, ada yang nomor-nomornya tinggal dikurangi dengan angka tiga, terus di geser ke kanan, dan diselipin angka tujuh di depan. Rata-rata meleset sedikit, dan mereka tidak sabar untuk memasang lagi dan memperbaiki strateginya untuk putaran minggu depan.
Pulang ke rumah, aku melihat ayah sedang berdiri di teras depan.
“Kamu dari warung Parjo lagi?” ayah bertanya.
“Iya, Ayah…,” aku agak gemetar dan berharap ayah tidak marah, “aku hanya menunggu nomor keluar saja.”
Ayah diam saja. Aku lega dan berjalan pelan ke dalam rumah, aroma wangi ikan asin merebak. Sepertinya ayah baru selesai memasak.
“Memangnya nomor yang keluar berapa?” Ayah tiba-tiba bertanya.
Aku agak kaget dan sedikit tersipu menjawab, “empat lima dua enam, Ayah.”
***
Aku terbangun dan tidak bisa tidur, suara ibu menggema, sepertinya ia kecewa dan marah sekali. Sesekali aku dengar ayah menjawab sesuatu. Pertengkaran kali ini terasa hebat, aku tak tahu apa kesalahan ayah atau apa kekesalan ibu. Kepalaku terasa pusing, dadaku sesak. Aku menoleh ke samping, dan berdoa agar Dimas tidak terbangun dan mendengar semua ini.
Aku mendengar langkah kaki ayah keluar menuju ruang tengah. Kemudian, aku berdiri, berjingkat dan mengintip dari balik pintu kamar. Ayah duduk di meja makan dengan sebatang lilin menyala disampingnya. Aku terenyuh melihat ayah merapihkan lembaran-lembaran uang koin-koin, dan beberapa lembaran kertas. Sepertinya ayah menghitung uang pembayaran cicilan buku yang ia jual di sekolah. Wajah ayah yang hampir tidak pernah marah itu tidak hanya terlihat lelah, tetapi juga terlihat tua.
Entah apa yang mendorongku berani melangkah keluar kamar dan mendekati ayah. Ayah kaget melihat aku berdiri di sampingnya, dan kertas-kertas yang ia pegang terlepas ke atas meja. Aku terkejut luar biasa melihat kertas-kertas itu. Aku terpana kaku tak mampu bicara. Dadaku kian sesak, kepalaku terasa berat.
“Iya, ayah orang yang kalah, dan kalah lagi, hari ini yang keluar empat lima dua enam,” setengah menggumam suara ayah terdengar pelan dan datar, lebih datar dari suara ayah yang biasanya memang datar. Ia tetap memandang nanar lurus ke depan. Tiba-tiba aku melihat butiran air menetes dari mata ayah. Tak pernah sekali pun aku melihat ayah meneteskan airmata.
Kepalaku terasa semakin pening dan berkunang-kunang, dadaku terasa sesak sesesak-sesaknya. Langkah kakiku terasa melayang ketika aku berjalan kembali ke kamar.
Pipiku terasa hangat oleh airmata, yang mengalir membasahi bantal. Aku menahan suara sekuat tenaga agar Dimas tidak terbangun. Tiba-tiba tanganku merasa disentuh. Aku menoleh ke samping, mata bening Dimas terbuka lebar.
“Kau terbangun, Dik?” aku berbisik bertanya dengan suara parau.
“Iya, Mas, aku selalu terbangun di tengah malam,” Dimas berbisik pelan.
Aku memiringkan badan, memeluk Dimas erat-erat, dan meraung sekeras-kerasnya hingga dadaku pecah.
—-
BACA JUGA
- Melintasi Embun
- Bidadari Yang Jatuh Dari Langit Montreux
- Angin Melayang Lewat Jendela Tak Berkaca
- Di Pesisir Malam Angin Beterbangan di Atap-atap Rumah, Bergentayangan di Pucuk-pucuk Kelapa
- Aku Melayang di Antara Sekumpulan Awan Malam Bermandikan Bintang
Salam, RF – www.FrindosOnFinance.com![]()