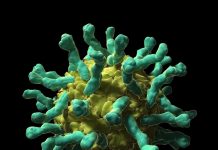Di pesisir malam angin beterbangan di atap-atap rumah, bergentanyangan di pucuk-pucuk kelapa, sebelum berlarian menuju pantai menggiring nelayan-nelayan kami perkasa
menerjang hitamnya samudra. Di pesisir malam angin menjadi sedikit keras, berdesiran daun-daun bambu dan kelapa di belakang rumah.
Ibu terlihat tak kunjung lelah. Ibu yang penuh cinta meski kadang aku seperlunya saja mencintainya. Dimana-mana ibu adalah sama, kekhawatirannya akan anak-anak yang dicinta bisa membuat anak laki-laki seperti aku menjadi muak. Dengar, mulutnya tak pernah berhenti berbusa dengan segala nasihat panjang berjelo-jelo, mengulang-ulang hal yang sama membuat telingaku berdenging. Persepsi ibu terhadap kematangan anaknya selalu jauh tertinggal dari usia si anak, anak ibu adalah selamanya anak-anak.
Aku sungguh lelah melihat ibu yang tidak kunjung lelah meski peluh menguyupi wajahnya. Sementara di pesisir malam angin makin kencang berlari. Aku mulai khawatir para angin tidak hanya menggiring nelayan-nelayan kami ke hamparan samudra, tapi mungkin mulai mengayun-ayun mereka di alunan gelombangnya.
Aku mulai mengeluarkan satu persatu barang-barang yang dikemas ibu, mie instan, minyak angin, bantal, selimut tebal. Ibu memang sering menyebalkan karena cintanya.
“Ibu, aku sudah bawa kain sarung dua, selimut ini Ibu simpan saja di rumah, ini kan selimut tidur Ibu.”
Sepasang mata itu menjadi begitu cemas, dan membujukku memasukkan barang-barang kemasannya kembali ke dalam tiga tas buntalan ini. Aku bergeming.
Tiba-tiba aku tertegun melihat sebuah sajadah biru.
“Ibu, ini kan sajadah Ayah buat Jumatan, pemberian Pak Haji Kali pulang dari Mekkah.”
“Kata Ayah, kamu bawa saja,” ujar Ibu, “ayah pernah bilang mau beli sajadah baru ke Padang.”
Hmmm, aku tidak percaya, pasti ibu memaksa ayah untuk memberikan sajadah ini untukku.
“Ibu, apa aku mesti pamit lagi sama Ayah esok pagi-pagi?”
Ibu diam saja.
“Tidak berbau telunjukku sedikitpun*),” ayah melengos begitu saja ketika aku sampaikan rencanaku merantau ke tanah Jawa. Jawaban ayah itu justru makin menguatkan hatiku. Ayah tidak pernah percaya padaku. Jadi, aku tidak akan pernah menjadi siapa-siapa di tanah pesisir ini. Ayah juga menolak dan tidak membolehkan aku mengurus salah satu kapal bagannya. Padahal ia sudah mulai sakit-sakitan, dan bagan yang satu lagi sudah diambil Uda Masri. Bulan lalu, dua-duanya ia berikan pada Uda Masri.
“Aku suruh menggarap sawah di kampung Tobi, kau tak mau. Kalau kau rajin dan pintar, kau sudah kubiayai kuliah seperti kakakmu si Ed. Kalau hendak melaut belum berbau telunjukku, ikut dan belajar sama si Masri saja dulu kau.”
Jam dinding berdentang-dentang dua kali, di pesisir malam angin tidak lagi berlari, mereka menderu berpacu bersama cahaya. Para angin nampaknya tak lagi sekedar mengayun-ayun nelayan kami, tapi barangkali mulai membolak-balik mereka seperti martabak dalam gelegak samudera.
ibu tiba-tiba menaruh jari telunjuk di mulutnya, mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, dan meletakkannya ke telapak tanganku.
“Ssst…ini satu dari simpanan ibu, bukan punya ayah, kau simpan baik-baik. Perjalananmu panjang dan jauh ke tanah seberang, dunia dengan segala hiruk pikuknya mungkin akan melukaimu berdarah-darah. Ketika kau terluka dan ibu tak berdaya di pedalaman pesisir ini, kau gunakanlah ini.”
Angin mulai memancing kemarahan kami orang pesisir, suara derak dahan patah menghempas keras ke dalam kolam ikan di belakang rumah.
***
Di Jakarta malam Tuhan menaburkan hujan tak henti-hentinya. Suara gemeretak air bocoran atap ke dalam ember di sudut kamar, menambah riuh gemuruh hujan di luar sana. Aku meraih sebuah map merah dari dalam lemari.
Pekan lalu, uda Masri menelpon.
“Pulanglah. Kalau kau tak mau berluluk di sawah, ambillah bagan ini satu. Anak-anak ular**) yang bagus-bagus aku carikan untukmu. Regok, teman SMPmu dulu, bisa kau andalkan mengurusi anak-anak ular.”
“Uda, coba nanti aku fikirkan lagi. Tapi, aku juga sayang meninggalkan toko di Cipulir yang sudah mulai ramai. Beberapa koran akhirnya akan menerbitkan tulisanku juga, aku dikabari kemarin-kemarin,” aku menjawab sambil menelan ludah kering, jawaban yang serupa dari waktu ke waktu. Aku tak tahu apakah uda Masri masih peduli dengan alasan-alasan yang aku berikan.
“Ibu semakin tua, sejak ayah meninggal dia menanyakan kau terus. Dan, kau tahu, sebelum meninggal Ayah juga berpesan kau supaya pulang. Ayah khawatir tentangmu.”
“Ah, Uda kan tahu ayah selalu begitu, ia tak pernah percaya kemampuanku. Aku baik-baik saja,” ludah keringku terasa pahit, pahit sekali.
Tapi aku membuka map merah ini bukan karena bujukan Uda Masri, mungkin juga bukan karena permintaan ibu atau pesan ayah. Tapi barangkali karena Ani. Selama ini dia yang menjadi sumber semangatku untuk bertahan, meski belakangan kami sering saling menghilang. Pagi tadi ia mampir ke kamar kontrakanku begitu saja, meski tak lupa membawa kue talam ketan srikaya untukku.
“Pulanglah,” katanya.
Aku hanya diam, sambil memperbaiki senar gitar.
“Pulanglah, sebelum Sodik kehilangan kesabaran dan orang-orangnya menemukanmu. Aku tahu kau tak akan pernah mampu melunasinya, dan jumlahnya terus bertumpuk. Apalagi kau melukai adik sepupunya waktu itu.”
“Aku tidak takut,” sergahku.
Tapi jantungku berdegup, dan telapak tanganku berkeringat.
“Pulanglah, karena aku akan pulang.”
Jantungku berhenti berdetak, aku tertegun dan berhenti menjalin tali gitar.
“Ke Sukabumi?”
Ia mengangguk pelan.
“Aku percaya dia orang yang baik dan bertanggung jawab, kalau tidak, tak mungkin ayah dan ibuku sedemikian sabarnya membujuk aku.”
Kami tak berani beradu pandang.
“Aku yakin, keluargamu pun akan memilihkan seseorang yang terbaik untukmu di negeri pesisir sana.”
Sekilas aku lihat ia berusaha tersenyum. Aku juga mencoba mengulas senyum, sebelum kami larut dalam diam yang teramat panjang.
Gemuruh hujan kian riuh, tetesan air bocoran atap di ember mulai memercik ke lantai. Aku duduk di bangku kecil sambil menggenggam sebuah bungkusan saputangan kecil, yang lama tersimpan dalam map merah itu bersama surat-surat berharga lainnya.
Angin kencang menghempaskan tempias ke pintu kamar. Aku melihat beberapa tetesannya mengalir ke dalam kamar dari bawah pintu. Bungkusan saputangan kecil ini makin erat kugenggam.
“Tidak berbau telunjukku sedikitpun,” masih terngiang-ngiang ucapan sinis dari ayah, yang justru memecutku untuk meninggalkan kampung untuk membuktikan bahwa dia salah. Tapi sepertinya dia benar, aku bukan siapa-siapa.
“Ayah tidak membencimu, tidak merendahkanmu. Ia memang begitu, ia hanya ingin yang terbaik buatmu, dan baginya merantau ke Jawa bukan yang terbaik untukmu,” Uda Masri suatu kali menenangkan hatiku. “Ia sangat sayang padamu. Aku yakin ia selalu mendoakanmu di setiap sujud sembahyangnya. Ayah tak pernah memakai sajadah baru yang ia beli di Padang waktu itu, ia selalu memakai sajadah tipismu itu hingga ia meninggal.”
Air bocoran atap memercik makin jauh dan membasahi kaos oblongku. Air tempias yang mengalir dari bawah daun pintu terus merambat hingga menggenang di telapak kakiku. Bungkusan kecil bersapu tangan dalam genggamanku ini basah kuyup oleh tetesan air mataku.
***
Hujan semalam masih menyisakan gerimis hingga pagi ini. Aku melangkah tergesa menyusuri lika-liku gang. Beberapa kali aku meraba kantong kiriku, meyakinkan bungkusan saputangan kecil itu masih di sana. Sebuah ojek terlihat mangkal di mulut gang, tapi aku memutuskan untuk terus berjalan saja ke halte bus.
Tiba-tiba aku mendengar deru sepeda motor persis di belakangku, sebelum sempat menoleh, aku terhempas terjerembab ke aspal keras. Perih dan ngilu, mataku berkunang-kunang. Aku melihat dua pasang kaki turun dari sepeda motor itu. Aku mencoba mendongak, meski samar aku mengenali dua wajah mereka.
Dalam kesakitan dan setengah sadar, tak banyak yang dapat aku lakukan ketika kaki-kaki itu menendang dan menginjakku. Sekilas aku lihat salah seorang dari mereka mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya. Ngilu dan sakit yang teramat sangat ketika ada yang terasa menghujam punggungku, aku hanya mampu mengerang dan merintih.
Dalam kesamaran aku melihat bungkusan kecil saputangan itu. Hanya sejengkal dari ujung jariku, tapi tak mampu kugapai. Bungkusan saputangan dari ibu itu tergeletak memerah dalam genangan darah bercampur gerimis hujan.
Kalimat itu masih terngiang di telingaku, di pesisir malam ketika angin berterbangan.
“Ssst…ini satu dari simpanan ibu, bukan punya ayah, kau simpan baik-baik. Perjalananmu panjang dan jauh ke tanah seberang, dunia dengan segala hiruk pikuknya mungkin akan melukai mu berdarah-darah. Ketika kau terluka dan ibu tak berdaya di pedalaman pesisir ini, kau gunakanlah ini.”
ibu memberikan salah satu miliknya yang paling berharga untukku, sebuah cincin emas hasil tabungannya bertahun-tahun.
“Ambillah, Nak, jaga ia baik-baik, karena ia akan membantu menjagamu ketika ibu tak ada. Ketika kau terjatuh, Nak, tak mampu berdiri, ketika tak satu pun bisa menolong mu di negeri jauh itu, juallah. Agar kau bisa berdiri dari jatuh, agar kau bisa pulang ke rumah kita, di negeri pesisir. Dan, kau tidak akan pernah gagal di mata ibu, meski kau kelak pulang melangkah terseok-seok di anak tangga dengan tubuh terluka karena kalah. Kau tidak pernah gagal di mata ibu, karena ibu mencintaimu.”
Nafasku tersengal, pandanganku kian buram, namun ibu terlihat makin jelas, mendekat dan mengulurkan kedua tangannya. “Ibu, aku pulang…” aku merintih dengan sisa-sisa nafas yang ada. Pelukan ibu terasa begitu hangat melenyapkan segala perih luka ketika aku hanya mampu terdiam, sama sekali terdiam.
***
————————-
*) Tidak berbau telunjuk = tidak percaya
**) Anak ular = anak buah kapal bagan
__________________________________________
*** Seri Pujangga:
- Melintasi Embun
- Bidadari yang Jatuh dari Langit Montreux
- Di Pesisir Malam Angin Beterbangan di Atap-atap Rumah, Bergentayangan di Pucuk-pucuk Kelapa
- * Aku Melayang di Antara Sekumpulan Awan Malam Bermandikan Bintang
Salam, Riki Frindos – www.FrindosOnFinance.com![]()