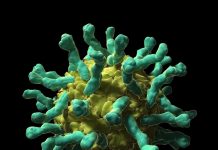Ayah sudah berdiri di sampingku, tersenyum – sedikit saja, dan mengacak-acak rambutku. “Ayo berdiri, mari melintasi embun.” Betul, ayah berjanji semalam, janji lama ayah yang tak pernah sempat tertepati. Subuh ini kami akan melintasi embun di lutut Gunung Sago, jauh dari tanah pesisirku yang berkelapa berombak.
Pintu rumah tua ini merintih berderit ketika kami melangkah keluar. Angin gunung menghujam-tikam dalam sekali ke pusat tulang. Aku mengikuti langkah ayah menuruni tangga kayu. Seekor kupu-kupu hinggap di bahu ayah. “Ayah seperti Aladin,” aku tertawa karena ayah membiarkan saja kupu-kupu itu rebah di bahunya.
“Ayah, embun mana?”
“Semuanya embun.”
“Semuanya?”
“Semuanya, dimana-mana,” ayah merentangkan tangan, menengadahkan kepala. “Embun membasah daun-daun, ranting-ranting, putik-putik, bunga-bunga. Embun di atas kepala kita, embun kita pijaki, embun kita hirup. Embun membaluri kita, embun menelusuri kita.”
Kami berbelok ke kiri, melangkah di atas rumput-rumput basah, melintasi sebuah rumah gadang bergonjong. Semak dan bunga-bunga liar basah di mana-mana.
“Dulu, hanya rumah datuk dan rumah gadang bergonjong itu. Sisanya adalah pohon, ilalang, pimping, bunga liar… Dulu, hanya datuk, nenek, ayah, Paman Betano, dan juga etek serta Mak Laiman. Sisanya adalah burung, ayam hutan, siamang, burung, burung, dan burung dimana-mana.”
Ayah memutar pandangannya ke sekeliling, aku pun ikut memutar kepala. Sepertinya aku melihat burung di balik rimbun gelap semak-semak itu.
“Dulu ini hutan.”
“Ayah dulu tinggal di hutan?”
Kami terus berjalan, menuju gelanggang. Rumpun pimping menyemak di sebelah kanan, dua rangkiang tegak bersebelahan.
“Dulu, ayah di atas rangkiang, datuk dan Paman Betano melemparkan karung padi ke atas.”
“Sampai penuh, Ayah?”
“Penuh.”
“Lalu bagaimana Ayah keluar?”
“Sebelum dua karung terakhir.”
Angin gunung tetap dingin ketika kami sampai di sisi gelanggang. Gelanggang luas, dilingkari tebing di sekelilingnya. Di gelap langit timur, sepercik fajar menjingga-merah, setitik bintang berpijar-mekar.
“Dulu, kuda-kuda berpacu di sini, di gelanggang ini. Kuda berpuluh berpacu berpeluh berdebu. Sekeliling tebing disesaki orang bersorak-sorai. Penjaja kacang goreng berteriak-teriak diantara gemuruh sorak-sorai. Bendera kuning, merah dan hitam berkibar-kibar. Lalu, datuk akan membelikan ayah sebungkus kacang goreng, sebungkus pula buat Paman Betano.”
“Waktu cepat berlalu, ” ayah menggumam pelan dan menengadahkan kepala memandang langit berbintang.
“Kenapa cepat, Ayah?”
“Karena kita tenggelam di dalamnya.”
“Tenggelam?”
Ayah melipat tangan ke dada. Sehelai daun gugur melayang menyentuh rambut ayah, sebelum berlabuh di rerumputan.
“Kau dengar suara air itu?”
“Iya, kudengar jelas, Ayah.”
“Adalah sungai itu di tengah rimbun pepohonan di seberang sana. Berhulu dari Gunung Sago, lalu menyatu dengan puluhan sungai lainnya, sebelum bermuara di Selat Malaka.”
“Selat Malaka? Jauh sekali.”
Aku mengikuti ayah duduk di tebing ini beralaskan rumput berembun.
“Di sungai itu ayah menunggu.”
“Ayah menunggu siapa?”
“Menunggu nenek dan Mak Laiman membawa bekal, membawa berita. Nenek dan Mak Laiman menunggu malam sepekat-pekatnya, menunggu kelam sehening-heningnya.”
“Ayah kenapa?”
“Ayah harus masuk hutan.”
“Bukankah Ayah dulu tinggal di hutan?”
“Ayah harus mencari hutan yang lebih jauh lagi, lebih rimbun lagi, lebih pekat lagi.”
“Ayah kenapa, sih?” aku sungguh heran ayah berjalan-jalan jauh ke dalam hutan.
“Ayah berperang.”
“Ayah berperang?”
Aku memutar duduk menghadap ayah. Ayah berperang! Hebat!
“Ayah berperang dengan siapa di hutan? Dengan Belanda?”
“Bukan.”
“Jepang?”
Ayah menggelengkan kepala.
“Masa ayah melawan Tarzan di hutan sih?”
“Ayah berperang melawan Tentara Pusat!” sekelebat asap putih di dingin pagi meluncur dari mulut ayah.
“Tentara Pusat? Mereka dari mana, Ayah?”
“Dari pusat.”
“Mereka jahat?”
“Mereka memasuki kampung-kampung, mereka mengacak rumah-rumah. Mereka membentak orang-orang, mereka menangkap orang-orang, mereka memukul orang-orang, mereka membunuh orang-orang. Mereka membunuh teman-teman ayah, mereka membunuh Paman Betano.”
Aku terkejut tiada kepalang, Tentara Pusat sungguhlah jahat.
“Jadi Tentara Pusat jahat, Ayah?”
“Tidak semuanya jahat.”
“Kenapa Ayah berperang dengan Tentara Pusat?”
“Karena mereka menumpas pemberontak, sementara ayah berjuang melawan tirani.”
“Tirani?”
Ayah memandang jauh ke seberang tebing itu, sepertinya ke sungai itu. Selintas bintang jatuh menyilang di langit, untuk kemudian tenggelam di pelukan rimbun pepohonan.
“Lalu, perang makin keras, Tentara Pusat berpuluh-puluh ribu memasuki negeri kita. Mereka ada di mana-mana. Laki-laki muda seperti ayah lari ke hutan. Yang tinggal ditangkap, atau harus bekerja sama dengan mereka. Ayah lari makin jauh ke dalam hutan. Berbulan-bulan lamanya ayah di hutan pekat belantara dan tidak kembali ke hutan kampung ini. Sampai hari itu…
“ Sampai hari itu, seseorang membawa selembar kertas. Pesan dari nenek: Ayah harus segera pulang, nenek akan menunggu di tepi sungai itu. Lalu, berhari-hari ayah dan dua orang teman merambahi hutan mencari jalan pulang. Sampai hari itu…”
Ayah terdiam dan mengusap matanya dan kemudian lanjut bercerita. “Sampai hari itu, di tepi sungai itu, seperti biasa di sepekat-pekatnya malam, di sehening-heningnya kelam. Nenek memeluk ayah dan menangis, etek menangis lebih keras lagi. Seisi hutan pastilah terbangun.”
“Kenapa semuanya menjadi sedih, Ayah?”
Tegak bangkit, ayah mengulurkan tangannya padaku. Ayah membimbing tanganku dan membawa langkah kami menaiki sebuah tebing kecil yang lebih tinggi sepinggang dari tebing gelanggang ini. Rumpun pimping dimana-mana, beberapa pohon bambu, bunga-bunga liar, dan suara jengkerik di beberapa sudut.
Aku tersentak, langkahku tertahan, aku menarik tangan ayah mundur. Aku sungguh takut pada orang mati. Gundukan tanah itu membuat aku merinding.
“Jangan takut,” ayah berujar pelan, “itu datuk.”
“Datuk?”
“Iya, waktu itu nenek dan etek menangis di tepi sungai itu. Kemudian, mereka membawa ayah ke sini, ke tebing ini. Ayah hanya bisa melihat gundukan tanah berpagar bambu. Datuk pergi menghadap Tuhan, tak pernah pamit.”
Suara ayah berubah sedikit parau. Aku mendongak, oh, ayah menangis. Air mata jelas bergulir di muka ayah.
“Ayah kenapa menangis?”
Aku belum pernah melihat ayah menangis. Aku menangis, aku sedih melihat ayah menangis.
“Ayah bertemu datuk terakhir kali di tepi sungai itu setahun sebelum datuk meninggal. Ayah marah pada datuk, ayah teriakkan sekeras-kerasnya bahwa datuk pengkhianat, bahwa datuk pengecut. Kemudian ayah menembakkan senapan ayah ke udara. Datuk kaget dan terlonjak, tapi ayah tidak peduli. Ayah kemudian berlari ke hutan, ayah marah, marah sekali.”
Ayah menengadahkan kepalanya memandang langit. Aku menggeser kaki merapat ke ayah.
“Datuk tidak pernah setuju ayah berperang, datuk tidak pernah setuju ada perang. Semuanya hanya akan berakhir dengan kesedihan, kata datuk. Datuk tidak mau kehilangan anak-anaknya lagi, cukup Paman Betano. Datuk tidak mau kehilangan teman-temannya lagi. Datuk mengajak semua berbicara dengan mereka, dengan orang pusat.”
Ayah menghela nafas panjang. Aku menggenggam tangan ayah.
“Tapi bagi ayah perjuangan harus diteruskan. Penindasan harus dibalas. Darah Paman Betano tidak akan pernah tertumpah sia-sia. Jika kita terlalu lunak dan pengalah mereka akan makin sewenang-wenang.”
Ayah mengusap airmata di pipinya. Ayah mengusap airmata di pipiku.
“Ayah tidak boleh memarahi datuk.”
“Iya, tidak boleh.”
“Ayah berdosa pada datuk.”
“Iya, ayah berdosa.”
“Ayah harus minta maaf pada datuk.”
Ayah tersenyum, membelai kepalaku, dan kemudian memagut aku.
“Tapi akhirnya Ayah menang perang ‘kan?”
“Sebelum beliau gugur, datuk meninggalkan pesan buat ayah lewat nenek. Bahwa darah harus berhenti ditumpahkan, bahwa perusakan kampung-kampung harus dihentikan, bahwa penyiksaan orang-orang harus dihentikan, bahwa penghinaaan perempuan kita harus dihentikan, bahwa anak-anak harus sekolah lagi. Bahwa mereka terlalu besar dan kejam untuk dilawan. Bahwa kita harus berhenti berperang. Namun apa? Datuk gugur juga di tangan mereka! Tentara Pusat itu menembak datuk!”
Tentara Pusat sungguh jahat sekali, teganya membunuh datuk.
“Ayah tidak menunggu pagi waktu itu. Ayah langsung memanggul senapan ayah, setengah berlari tergesa menyusuri sungai.”
“Ayah berlari kemana?”
“Ayah akan mendatangi markas Tentara Pusat. Ayah hapal betul liku-liku kampung ini. Dan tanpa Tentara Pusat sadari, ayah sudah berada di samping markas mereka. Beberapa orang Tentara Pusat, yang berdiri berjaga terkantuk-kantuk, kaget dan kebingungan melihat kemunculan ayah. Ayah tidak menunggu sedetik pun, segera mengangkat senapan ayah.”
“Ayah tembak mereka semua ‘kan? Semuanya mati, Ayah? Orang-orang yang membunuh datuk dan Paman Betano itu mati berdarah-darah semuanya ‘kan? Ayah menang!”
“Ayah angkat senapan ayah ketika mereka masih kaget dan kebingungan. Mereka inilah gerombolan yang membunuh datuk, yang membunuh Paman Betano, yang membunuh teman-teman ayah. Tak ada lagi yang bisa ayah lakukan untuk datuk…”
“Pasti musuh ayah satu markas mati semua ! Ayah hebat!”
“Tak ada lagi yang bisa ayah lakukan untuk datuk kecuali ayah mengangkat senjata ayah, dan menyerahkannya pada Tentara Pusat yang kebingungan itu. Tak ada lagi yang bisa ayah lakukan untuk datuk. Ayah menyerah, berlutut, dan menumpahkan airmata di hadapan mereka. Datuk mungkin benar, mereka memang terlalu besar dan kejam untuk dilawan. Kita terpaksa bicara dengan mereka, meski berarti kita kalah.”
Seekor elang melengking dan melayang di atas kepala kami. Pimping-pimping bergoyang, bambu-bambu bergetar, kupu-kupu bertebaran beterbangan. Pagi dingin dalam embun.
“Waktu cepat berlalu,” ayah menggumam.
“Karena kita tenggelam ‘kan, Ayah?”
***
In memoriam my late father, N. Datuk Parmato Alam
((cerita pendek ini pernah diterbitkan dalam buku kumpulan cerpen dari penerbit KOMPAS))
*** Seri Pujangga:
- Angin Melayang Lewat Jendela Tak Berkaca
- Bidadari yang Jatuh dari Langit Montreux
- Di Pesisir Malam Angin Beterbangan di Atap-atap Rumah, Bergentayangan di Pucuk-pucuk Kelapa
- * Aku Melayang di Antara Sekumpulan Awan Malam Bermandikan Bintang
Salam, Riki Frindos – www.FrindosOnFinance.com![]()